Wacana Perda Anti-LGBT membuka ruang legitimasi diskriminasi sistemik terhadap minoritas gender dan seksual. Gagasan ini mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara, seperti kebebasan berekspresi dan rasa aman. Alih-alih melindungi hak asasi manusia dan mempromosikan keadilan sosial, pemegang kebijakan memperlihatkan ketidakmampuan dalam menghadapi kompleksitas isu gender dan seksual.
Di tengah kesunyian kontrakan, Ira menemukan hiburan di media sosial. Ia menikmati konten komedi dan kuliner, hingga tiba-tiba sebuah video menarik perhatiannya. Di layar ponsel, sosok perempuan dengan nada tegas dan percaya diri muncul, meninggalkan kesan yang kuat. Perempuan itu adalah Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana.
Namun, kesan kuat itu berubah menjadi kekecewaan tatkala Eva berbicara. Di hadapan jurnalis, Eva menyatakan tekadnya untuk menciptakan Bandar Lampung yang bebas LGBT. Ia memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan, dari RT hingga babinkamtibmas, untuk mengawasi setiap pertemuan yang mencurigakan.
Rencana untuk menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Larangan Aktivitas LGBT juga dikemukakan Eva. Langkah ini sebagai upaya melindungi moral, budaya, dan agama masyarakat, terutama generasi muda, dari pengaruh yang dianggap tidak sesuai.

Ira terperenyak, tak percaya perkataan keras itu keluar dari mulut seorang kepala daerah. Baginya, pernyataan Eva seperti memberikan legitimasi untuk melakukan kekerasan dan persekusi terhadap kelompok minoritas gender dan seksual, seperti dirinya.
“Apa maksudnya menghilangkan LGBT? Apakah kelompok minoritas seperti kami mau dimusnahkan?” Ira bertanya dengan nada yang penuh kekhawatiran.
Ira makin penasaran. Ia mencari informasi lebih lanjut melalui media sosial dan mesin pencari, dan hasilnya membuat terkejut. Ternyata, Eva bukan satu-satunya yang menyerukan penghilangan LGBT. Banyak wakil rakyat, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil mengecam keberadaan LGBT, menyebutnya sebagai penyebab HIV-AIDS dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Ira merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Ia tak percaya bahwa orang-orang yang seharusnya melindungi dan melayani masyarakat justru menyerukan kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Ia membaca bahwa BEM Universitas Lampung bahkan berkampanye dengan mencuplik berita yang menyatakan LGBT lebih berbahaya daripada terorisme dan narkoba.
Ira juga menemukan informasi bahwa DPRD Lampung sedang mematangkan Perda Anti-LGBT. Inisiatif ini mendapat dukungan dari Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela. Ia berharap, perda itu dapat menjadi landasan hukum untuk mengatur dan memberi sanksi terhadap perilaku yang dinilai menyimpang.

Melihat berbagai pemberitaan tersebut, Ira seperti hidup di negara yang tidak memiliki ruang untuk perbedaan dan kebebasan. Ketakutan dan ketidakamanan menghantuinya. Bahkan, ia harus menggunakan jaket tertutup dan masker untuk menyembunyikan penampilannya sebagai transpuan.
Kecemasan Ira meningkat karena teringat kejadian pada 2018. Tiga transgender di Pesisir Barat pernah menjadi korban perlakuan tak manusiawi oleh Sat Pol PP. Mereka ditangkap dan disemprot dengan mobil pemadam kebakaran, lalu dipaksa berpose bersama dalam upaya mempermalukan dan merendahkan martabat.
Memori itu membuatnya merasa rentan dan waswas akan keselamatan. Bagaimana pemerintah bisa membiarkan perlakuan tak manusiawi terhadap warganya sendiri?
Pada tahun yang sama, Pemkab Pesisir Barat menerbitkan surat edaran yang melarang aktivitas LGBT, seakan-akan mereka tidak memiliki hak untuk hidup dengan martabat. Ira merasa hal ini tak adil, karena para transpuan juga berhak mendapat perlakuan yang sama: bebas dari diskriminasi, kekerasan, penyiksaan, serta dihormati sebagai manusia yang setara.
Razia menyasar LGBT pun terjadi di Bandar Lampung pada 2019. Dengan dalih menciptakan ketertiban umum, Sat Pol PP menangkap tiga transpuan, meninggalkan kesan bahwa keberadaan mereka tidak diinginkan.
Kelompok minoritas gender dan seksual kerap menerima perlakuan diskriminatif di tengah masyarakat. Ira merasakan hal ini secara langsung. Sejak menjadi transpuan pada 2018, ia tidak pernah bisa bekerja di sektor formal karena penampilan yang berbeda dengan kebanyakan orang. Ira pun menjadi tukang pijat untuk bertahan hidup. Namun, banyak dari kelompok minoritas gender dan seksual menempuh jalan lebih sulit: pekerja seks komersial.
Ira juga merasakan ketakutan yang sama seperti banyak transpuan lainnya. Ia ragu untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi karena khawatir menjadi korban bullying. Ketakutan ini diperparah dengan terbatasnya akses layanan kesehatan bagi mereka. Tanpa KTP yang sesuai dengan identitas, Ira dan banyak transpuan lainnya merasa seperti tidak memiliki harkat.
Di tengah semua permasalahan tersebut, Ira tak dapat membayangkan bila peraturan daerah itu benar-benar absah. Komunitasnya bisa semakin tersingkir dari kehidupan masyarakat. Hak-hak mereka akan terus terabaikan.
Ia bilang, kelompok minoritas gender dan seksual tak banyak menuntut. Mereka hanya ingin pemerintah dan masyarakat menaruh rasa hormat. Setiap orang boleh tidak setuju dengan orientasi seksual seseorang, namun bukan berarti tak menghargainya sebagai manusia.
Ira meminta pemerintah mempertimbangkan ulang rencana penyusunan perda tersebut. Ia tidak ingin regulator kebijakan mempertebal stigma dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas gender dan seksual. Lebih buruk lagi, pemerintah justru merenggut hak asasi warganya atas nama moral, norma sosial, dan agama.
***
Kekhawatiran soal rancangan Perda Anti-LGBT juga menghantui Ai, seorang instruktur kebugaran. Ia mendengar rencana tersebut dari kawan-kawannya. Ai cemas, orang tua yang sudah menerima kondisinya, bakal kembali mempersoalkan orientasi seksualnya sebagai gay.
Memori perjuangan untuk meyakinkan orang tuanya masih terasa nyata. Ia ingat bagaimana harus menjelaskan bahwa setiap manusia lahir dengan keunikan tersendiri, termasuk dalam ketertarikan seksual.
Awalnya, orang tua kaget dan menentang. Lewat proses panjang dan berat, orang tua pun bisa menerima. Namun, dengan rancangan Perda Anti-LGBT, Ai khawatir bahwa semua yang telah dicapai akan sia-sia.
Ai melihat penerbitan Perda Anti-LGBT hanya memperpanjang rantai stigma dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas gender dan seksual. Masyarakat masih terjebak dalam pemahaman yang keliru, memandang LGBT sebagai penyakit dan penyimpangan.
Mereka yang berani menunjukkan ekspresi berbeda dari norma sosial akan dicap sebagai LGBT. Padahal, orientasi seksual dan identitas gender adalah dua entitas berbeda. Lesbian, gay, dan biseksual, merupakan orientasi seksual. Sementara, transgender adalah identitas gender.
Menjadi transgender tidak ada hubungannya dengan orientasi seksual. Seseorang bisa menjadi transpria dan menjadi gay – atau menjadi transpuan dan menjadi lesbian. Artinya, tidak ada ukuran pasti untuk menentukan orientasi seksual seseorang, kecuali orang tersebut mengakuinya.
Berbeda dengan Ira yang memilih identitas gender sebagai transpuan, Ai tetap menunjukkan penampilan seorang pria. Sepintas, tidak ada perbedaan Ai dengan lelaki lainnya, yang membedakan hanyalah ketertarikan seksual. Jadi, penerapan perda tersebut akan serampangan.
“Setiap orang yang berbeda secara penampilan akan dicap sebagai LGBT walaupun belum tentu mereka melakukannya,” kata Ai.
Di samping itu, Ai tidak setuju dengan klaim bahwa LGBT adalah penyakit. Baginya, orientasi seksual merupakan hal alami, bukan sesuatu yang dapat ditularkan. Ia telah bergaul dengan banyak orang heteroseksual yang dianggap “normal” oleh masyarakat, namun tak satupun dari mereka yang berubah orientasi seksualnya. Pengalaman ini meyakinkannya bahwa orientasi seksual bukanlah sesuatu yang dapat dipengaruhi atau diubah oleh lingkungan sekitar.

Bahkan, American Psychiatric Association (APA) telah menghapus homoseksualitas dari Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental sejak 1973. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi seksual bukanlah penyakit mental. Dengan demikian, narasi yang menyebut LGBT sebagai penyakit hanya sikap apriori.
Tak hanya itu, World Health Organization (WHO) juga telah mengambil langkah serupa. Organisasi kesehatan dunia ini secara tegas menyatakan bahwa homoseksualitas tidak bisa dianggap sebagai kondisi patologis, kelainan, atau penyakit. Penelitian secara biologis dan psikologis menunjukkan bahwa orientasi seksual adalah bagian intrinsik dari karakteristik pribadi manusia.
Pada 2018, WHO menetapkan International Classification of Diseases (ICD) 11, yang secara jelas menyatakan bahwa homoseksualitas dan disforia gender bukan gangguan jiwa. Dengan demikian, semakin jelas bahwa orientasi seksual dan identitas gender bukanlah sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai penyakit atau gangguan mental.
Pedoman Penggolongan & Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pun menyebut bahwa homoseksualitas bukan gangguan jiwa.
Ai menyayangkan bahwa kelompok LGBT kerap dijadikan kambing hitam atas segala bencana yang terjadi di masyarakat, terutama pada kasus HIV-AIDS. Banyak yang mengaitkan LGBT dengan tingginya angka penularan HIV, seolah-olah mereka adalah sumber peningkatan penyebaran infeksi menular seksual (IMS) dan HIV.
Padahal, penularan HIV dan IMS disebabkan oleh perilaku berisiko seksual yang bisa terjadi pada siapa saja, bukan hanya LGBT. Artinya, baik orang heteroseksual maupun homoseksual dapat terkena HIV apabila tidak menerapkan standar keamanan, seperti menggunakan alat kontrasepsi dalam perilaku seksualnya. Dengan demikian, stigma semacam itu justru akan mengalihkan perhatian dari akar masalah HIV, yaitu perilaku seks berisiko menjadi masalah orientasi seksual.
Atas sejumlah persoalan itu, Ai berharap pemerintah bisa lebih bijak dalam merumuskan aturan yang adil dan inklusif. Sebagai regulator kebijakan, pemerintah seyogianya menjamin, melindungi, dan menghormati hak setiap warga negara tanpa memandang perbedaan apapun, termasuk orientasi seksual dan identitas gender.
Dengan demikian, negara benar-benar hadir dalam mengentaskan rantai diskriminasi yang tak kunjung putus. Memberikan ruang yang aman bagi setiap individu untuk hidup dengan martabat dan harga diri. Harapan ini bukanlah sekadar impian, melainkan kebutuhan mendasar bagi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan beradab.
Kejahatan Kemanusiaan
Data Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) semakin memperjelas pernyataan Ai. Sepanjang 2017-2018, sebanyak 1.226 orang menjadi korban stigma, diskriminasi, dan kekerasan berbasis orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender. Mereka tersebar di berbagai wilayah dengan jenis stigma, diskriminasi, dan kekerasan yang beragam dan menyakitkan.
Transgender menjadi kelompok paling terdampak, dengan 726 orang menjadi korban. Diikuti oleh kelompok LGBT secara umum sebanyak 234 orang, kelompok gay sebanyak 228 orang, dan kelompok lesbian 34 orang. Sisanya dikategorikan sebagai korban lain-lain, menunjukkan bahwa dampak diskriminasi tidak terbatas pada satu kelompok saja.
Pelbagai stigma yang melekat pada mereka di antaranya bertentangan dengan agama, menyimpang, merusak generasi muda, individu berbahaya, sumber penularan HIV dan AIDS, penyakit, hingga penyebab bencana alam.
Menurut LBHM, rentannya diskriminasi, stigma, dan kekerasan oleh masyarakat dipengaruhi oleh pemerintah dan penegak hukum. Mereka berlomba-lomba membuat peraturan diskriminatif terhadap kelompok LGBT.
Komunitas LGBT juga kerap menjadi korban perlakuan tak manusiawi, seperti rukiah dan terapi konversi. Bahkan, beberapa digundul secara paksa dan diperlakukan hina, dengan dalih bahwa cara tersebut dapat mengembalikan mereka ke “jalan yang benar.”
Selain stigma, kelompok minoritas gender dan seksual juga sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi, seperti persekusi, upaya paksa dan pemidanaan, pelarangan pendidikan, pembubaran acara, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. LBHM membedakan antara persekusi dan upaya paksa serta pemidanaan.
Persekusi adalah tindakan perampasan hak yang didasarkan pada perbedaan orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender, sesuai dengan definisi persekusi dalam Statuta Roma. Sementara itu, upaya paksa dan pemidanaan merupakan tindakan aparat dalam penegakan hukum pidana, seperti menerapkan UU 4/2008 tentang Pornografi, UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta pasal pemalsuan dokumen dalam KUHP.
Salah satu kasus terbaru terkait persekusi dan kriminalisasi terhadap kelompok LGBT terjadi di Bogor. Pada 22 Juni 2025, Polsek Megamendung dan sejumlah anggota ormas yang tidak dikenal membubarkan acara bertajuk Big Star Got Talent. Polisi kemudian menggiring 75 orang ke polsek, lalu memindahkannya ke Polres Bogor. Mereka dijerat dengan pasal-pasal pidana, termasuk Pasal 7 dan 10 UU Pornografi serta Pasal 296 KUHP. Tuduhannya: menggelar pesta seks.

Namun, hasil pendampingan LBHM menemukan bahwa tidak ada perbuatan seksual atau unsur pornografi dalam acara tersebut. Kegiatan komunitas terdiri atas lomba menyanyi, pertunjukan busana, dan tari, sama seperti komunitas heteroseksual lainnya. Polisi tidak menemukan bukti yang mendukung dugaan pornografi, dan dokumentasi penertiban tak menunjukkan ketelanjangan. Kondom yang ditemukan dalam keadaan belum terpakai, dan kontrasepsi bukanlah bukti pidana, melainkan alat kesehatan.
LBHM melihat sentimen, kebencian, dan ancaman terhadap LGBT telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu kejahatan kemanusiaan. Pola pelanggaran ini dimulai dari stigma yang melekat pada masyarakat, yang kemudian terinternalisasi dalam konstruksi sosial. Masyarakat mulai melabeli LGBT sebagai “bukan golongan mereka”, yang kemudian meningkat menjadi kebencian, penolakan, dan perampasan hak-hak dasar.
Menurut International Criminal Court (ICC), persekusi dalam kejahatan kemanusiaan memiliki beberapa unsur yang jelas. Misalnya, pencabutan atau perampasan hak dasar yang parah dan bertentangan dengan hukum internasional, penyasaran terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan identitas atau kolektifitas, dan tindakan persekusi yang dilakukan sebagai bagian dari serangan sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil. Dalam konteks ini, sentimen dan kebencian terhadap LGBT dapat dianggap sebagai awal dari kejahatan kemanusiaan yang dapat memiliki dampak yang sangat besar dan berkepanjangan.
Persekusi terhadap kelompok LGBT telah menjadi kenyataan pahit, dengan praktik-praktik diskriminatif yang merajalela di dunia pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Hak-hak dasar mereka terus-menerus diancam. Kasus penangkapan 141 orang di Atlantis dan penggerebakan terhadap 75 orang di Bogor menjadi contoh nyata bagaimana privasi dan kebebasan mereka dilanggar.
Pelaku persekusi sering kali menyasar orang atau kelompok LGBT hanya karena identitas mereka. Perbedaan orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender menjadi alasan untuk membenci dan menyerang. Indikasi bahwa persekusi ini dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik terhadap kelompok LGBT juga tampak kuat. Praktik stigma, diskriminasi, dan pelanggaran HAM terjadi secara teritorial dan sistematis.
Namun, yang lebih memprihatinkan adalah peran negara. Pembiaran dan pengabaian dari negara, termasuk mengambil kebijakan diskriminatif seperti Perda Anti-LGBT, membuat khawatir bahwa kelompok minoritas gender dan seksual akan terus menjadi target kejahatan kemanusiaan di masa mendatang.
***
Kebencian yang Dilembagakan
Peneliti Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Lampung Dodi Faedlulloh mengatakan, Rencana Perda Anti-LGBT perlu menjadi perhatian serius dalam diskursus demokrasi dan HAM. Kebijakan semacam itu bukan hanya problematik secara hukum dan etika, tetapi juga mencederai prinsip dasar negara hukum yang menjamin kebebasan individu dalam ruang privat.
Dodi menekankan bahwa negara, termasuk pemerintah daerah, tidak memiliki otoritas moral maupun legal untuk mengatur orientasi seksual warganya. Orientasi seksual adalah bagian dari identitas pribadi yang tidak bisa dijadikan objek intervensi negara, apalagi dikriminalisasi.
“Upaya untuk membatasi atau menstigmatisasi kelompok LGBT lewat perda justru memperlihatkan bagaimana kebijakan publik bisa digunakan sebagai alat represi, bukan perlindungan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi tersebut. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa kelompok minoritas seksual terus menghadapi diskriminasi dan kekerasan tak berkesudahan.

Kebijakan diskriminatif seperti Perda Anti-LGBT membuka ruang legitimasi bagi kekerasan sosial dan persekusi. Mereka kerap mengalami pengusiran, pembubaran acara, bahkan kekerasan fisik dan psikologis, yang sering kali dilakukan atas nama “moralisasi publik.” Alih-alih melindungi hak warga, negara justru menjadi pelaku utama dalam mendefinisikan siapa yang dianggap “normal” dan siapa yang harus disingkirkan.
Dodi bilang, prinsip inklusivitas harus menjadi fondasi kebijakan publik di masyarakat yang plural dan demokratis. Dalam sebuah negara yang majemuk, setiap warga berhak mendapatkan perlakuan sama dan adil, tanpa terkecuali. Negara seyogianya menjamin hak atas rasa aman, pelayanan publik, dan penghidupan layak bagi semua warga, termasuk komunitas LGBT. Negara bukan lembaga moral agama tertentu, melainkan institusi yang bekerja atas dasar konstitusi dan hak asasi manusia.
Ketimbang menggagas perda diskriminatif, pemerintah daerah lebih baik fokus pada pemenuhan hak dasar warga. Pendidikan berkualitas, kesehatan terjangkau, lapangan kerja yang layak, dan perlindungan hukum secara efektif mesti menjadi prioritas utama. Dengan demikian, setiap warga negara dapat hidup dengan bermartabat dan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan masyarakat.
Isu moralitas tidak bisa dijadikan dalih untuk menindas warga negara yang berbeda. Justru di sinilah letak ujian demokrasi: apakah negara mampu bersikap adil dan melindungi hak kelompok minoritas, sekalipun berbeda dari arus mayoritas?
Dalam konteks ini, upaya merumuskan atau mempertahankan Perda Anti-LGBT tak hanya menyesatkan secara kebijakan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, keberagaman, dan semangat konstitusi negeri ini.
“Sudah saatnya mendesak agar kebijakan publik dibangun atas dasar kesetaraan, bukan ketakutan dan kebencian yang dilembagakan,” kata Dodi.
Akar Diskriminasi
Sosiolog dan aktivis keragaman gender Dede Oetomo memandang bahwa akar diskriminasi dan represi terhadap kelompok minoritas gender dan seksual adalah sikap intoleransi. Pemerintah dan masyarakat masih gagap dalam menghadapi perbedaan. Sehingga, mereka yang minoritas acap dipandang rendah dan tidak berhak mendapatkan perlakuan sama sebagai warga negara. Fenomena ini terjadi di berbagai dimensi, mulai dari agama hingga orientasi seksual.
Dede mencontohkan bagaimana kelompok agama tertentu kerap menjadi korban kekerasan dan persekusi hanya karena dianggap berbeda dari agama mayoritas. Masyarakat Papua juga sering mengalami diskriminasi rasial ketika menyuarakan pendapat. Fenomena ini berkaitan erat dengan sejarah sosial-politik dan budaya masa lalu, terutama pascaruntuhnya rezim Orde Baru yang melahirkan aksi diskriminatif kelompok mayoritas terhadap minoritas.
Tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas tidak hanya dilakukan individu, tetapi juga oleh kelompok-kelompok yang beroperasi secara terbuka maupun terselubung di balik aturan hukum dan kelembagaan negara. Motif kekerasan tersebut sangat beragam, mulai dari isu etnis, agama, ras, hingga seksualitas.
Pada masa lalu, negara membiarkan kekerasan tersebut, bahkan memberikan legitimasi politik dan hukum yang memperparah situasi. Budaya kekerasan ini masih berlanjut sampai sekarang, di mana mereka yang dianggap berbeda sering dikucilkan atau disingkirkan.
Penulis buku “Memberi Suara Pada yang Bisu” itu mengatakan, penentangan terhadap kelompok LGBT sering didasarkan pada dalih bahwa mereka tidak sesuai dengan Pancasila, agama, dan budaya. Anggapan ini muncul dari penafsiran sempit terhadap sila pertama Pancasila, “Ketuhanan yang Maha Esa”, yang diartikan bahwa setiap perbuatan harus sesuai dengan ketentuan agama. Dengan demikian, perbuatan yang bertentangan dengan agama dianggap bertentangan dengan Pancasila. Dalam konteks LGBT, banyak penafsiran agama yang menganggapnya sebagai dosa, sehingga secara otomatis dianggap bertentangan dengan Pancasila.
Namun, prinsip-prinsip Pancasila sebenarnya menempatkan hak asasi manusia sebagai prinsip dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, menegaskan pentingnya penghargaan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai manusia, serta keadilan bagi kelompok masyarakat yang lemah. Oleh karena itu, sebagai kelompok rentan, LGBT sepatutnya mendapatkan perlindungan negara dan perlakuan yang adil di masyarakat.
Terkait budaya, Dede mengungkapkan dalam bukunya bahwa anggapan LGBT, khususnya homoseksual, berasal dari Barat adalah tidak tepat. Banyak penelitian empiris telah menunjukkan keragaman gender dan penerimaannya di masyarakat Indonesia.
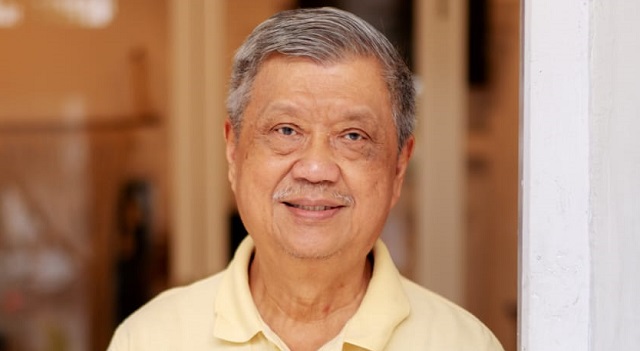
Contohnya, sarjana ahli Aceh, C. Snouck Hurgronye, melaporkan bahwa laki-laki Aceh memiliki tradisi menggemari budak dari Nias yang berperan sebagai penari (sadati) dan “disuruh melayani nafsu tak alamiah orang-orang Aceh.” Puisi sadati terkenal karena erotismenya, dengan beberapa bagian yang jelas-jelas mengacu pada hubungan kelamin sesama jenis.
Di Minangkabau, dikenal percintaan antara laki-laki yang lebih tua (induk jawi) dengan remaja laki-laki (anak jawi). Tampaknya, pranata “induk-anak” ini erat berkait dengan kebiasaan tidur di surau untuk anak-anak laki-laki yang sudah akil balig.
Di Jawa, pelembagaan homoseksualitas pada hubungan warok-gemblak, terutama di Ponorogo. Sang warok (lelaki dewasa) memelihara gemblaknya (remaja) berdasarkan kontrak dengan orang tua sang gemblak. Ia melakukan hal itu demi ilmu kesaktian (kanuragan) yang mewajibkannya menjauhi perempuan. Jika tak mencari kesaktian, warok beristri dan memiliki keturunan. Pernah ada warok-gemblak lesbian di Ponorogo.
Pelembagaan homoseksualitas di Jawa juga terlihat dalam pentas kesenian, seperti ludruk dan gandrung. Kemudian, terdapat bukti bahwa tarian seperti bedhaya dahulunya senantiasa dibawakan remaja laki-laki yang lemah gemulai (kewanitaan).
Di Pulau Bali, pada akhir abad ke-19, seorang pejabat kesehatan bernama Dr. Julius Jacobs menyaksikan kesenian gandrung yang unik. Penari gandrung, yang biasanya adalah bocah laki-laki berusia 10-12 tahun, tampil dengan pakaian wanita dan gerakan yang genit. Laki-laki yang menonton ikut menari dan mencium penari gandrung, serta memberinya uang kepeng sebagai tanda apresiasi.
Jacobs melaporkan bahwa kebiasaan ini dianggap biasa oleh masyarakat Bali pada saat itu. Tidak ada yang menutup-nutupi atau merasa malu. Bahkan, Jacobs menemukan pasangan-pasangan homoseksual yang hidup bersama secara terbuka.
Di Makassar, suku Bugis telah lama merayakan keragaman gender yang melampaui batasan biner tradisional. Dalam tradisi Bugis, dikenal lima kategori gender yang unik: perempuan (makunrai), laki-laki (uruane), calabai (orang yang mendekati perempuan), calalai (orang yang mendekati laki-laki), dan Bissu (orang yang berkelamin dan bergender ambigu). Konsep lima gender ini bahkan tercatat dalam kitab kuno La Galigo, sebuah puisi epik yang menceritakan mitos penciptaan dalam peradaban Bugis.
Erotisme homoseksual yang ditemukan dalam kebudayaan-kebudayaan tradisional membuktikan bahwa fenomena ini telah menjadi bagian integral dari berbagai suku bangsa besar di Nusantara, seperti Jawa, Bugis, Bali, Toraja, Dayak, Minangkabau, Papua, Madura, dan Aceh. Fakta ini membantah asumsi bahwa keragaman gender dan seksualitas adalah produk “budaya liberal.” Sebaliknya, keragaman tersebut bagian tak terpisahkan dari sejarah dan budaya Nusantara.
Keragaman gender telah menjadi bagian dari kehidupan sosial-budaya di Nusantara. Namun, Dede menekankan bahwa kunci untuk memutus rantai diskriminasi terhadap kelompok minoritas gender dan seksual terletak pada satu hal penting: menghargai perbedaan dan menerima keberadaan kelompok LGBT sebagai manusia yang setara.
“Kendati memiliki orientasi seksual berbeda, mereka tetaplah manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dijamin haknya sebagai warga negara,” kata Dede.(*)
Laporan Derri Nugraha
Liputan ini mendapat dukungan dari Yayasan Kurawal sebagai upaya memperkuat demokrasi.









