Kenaikan penghasilan anggota DPR di tengah kesulitan ekonomi rakyat memperlihatkan logika sungsang bernegara. Praktik oligarki ini bukan hanya memperdalam kesenjangan sosial, tetapi juga memperkuat struktur kekuasaan yang tidak akuntabel dan transparan. Di tangan segelintir orang, demokrasi dijadikan alat melegitimasi kekuasaan elite, bukan instrumen melayani kepentingan orang banyak.
Menjelang tengah malam, jantung Kota Bandar Lampung perlahan meredup. Kendaraan yang lalu lalang di kompleks Pasar Tengah semakin menipis, meninggalkan kesunyian yang hanya dipecahkan oleh suara-suara samar dari kejauhan.
Di atas bekas spanduk tipis yang tergulung di tanah, Rohmah (38) dan ketiga anaknya melepas lelah. Sehari penuh mereka berkeliling kota, mencari barang bekas yang bisa ditukar dengan rupiah. Tanpa dinding yang melindungi, tanpa atap yang menaungi, dan tanpa selimut yang menghangatkan, mereka beristirahat. Dalam keheningan malam, Rohmah berharap bahwa hari esok akan membawa secercah harapan.
Sementara, sang suami yang hidup dengan disabilitas fisik masih menyusuri jalanan. Ia tahu bahwa banyak perusahaan tidak mau memberinya kesempatan bekerja karena fisiknya, sehingga harus mencari nafkah dengan cara lain.

Empat tahun terakhir, Rohmah dan keluarganya hidup di jalanan. Mereka sempat menyewa sebuah kontrakan. Namun, kondisi ekonomi yang semakin memburuk setelah Pandemi Covid-19 membuat mereka tak mampu membayar uang sewa. Akhirnya, keluarga Rohmah hidup berpindah-pindah, mencari tempat yang aman untuk beristirahat.
Rohmah punya delapan anak, namun hanya tiga yang tinggal bersamanya. Lima lagi merantau ke kota seberang, putus sekolah, dan mencari pekerjaan apa saja. Beberapa di antaranya mengais rezeki dari belas kasihan orang.
“Bisa makan dan minum saja sudah syukur,” kata Rohmah.
Di balik kesulitan hidup, Rohmah berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saat ini, dua anaknya menempuh sekolah dasar. Ia menyimpan pakaian dan alat-alat sekolah mereka di sebuah toko kecil tak berpenghuni.
Toko itu gelap. Bau pesing. Dinding-dinding kusamnya menjadi saksi bisu kehidupan mereka yang penuh perjuangan.
Rohmah harus menyetor sejumlah uang agar bisa memakai toko tersebut. Meski membayar, mereka harus pergi tatkala toko itu buka pada pagi hari.
Kedua anak Rohmah bersekolah dengan jalan kaki. Ia membekali mereka dengan nasi putih dan uang jajan untuk membeli lauk. Setelah memastikan anaknya berangkat, barulah Rohmah berkeliling mencari rongsok.
Dengan segala keterbatasan, Rohmah bertekad memperjuangkan pendidikan anak-anaknya. Ia tak ingin mereka mengikuti jejaknya sebagai pemulung. Ia berharap, suatu hari nanti anaknya bisa memiliki kehidupan yang mereka impikan – tidur di rumah dengan kasur yang layak, mengantar anaknya sekolah dengan kendaraan, tanpa harus capek berjalan kaki.
Akan tetapi, kenyataan berkata sebaliknya. Kondisi ekonomi kian menurun, harga barang pokok membumbung tinggi, dan mencari uang semakin sulit. Hasil memulung kadang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia harus mengandalkan belas kasihan orang yang lewat, yang kadang-kadang memberi bungkusan makanan. Deru mesin di jalanan menjadi latar belakang kehidupan sehari-harinya.
Di sekitar daerah itu, setidaknya delapan keluarga yang hidup seperti Rohmah. Mereka tidur di trotoar, emperan toko, atau bawah jembatan. Anak-anak mereka bermain di jalan, sementara orang tua mencari nafkah dengan cara apa saja. Bau sampah dan kotoran menjadi aroma familiar.

Ketika mendengar kabar kenaikan penghasilan anggota DPR, Rohmah hanya menghela napas panjang. Ia membayangkan bagaimana wakil rakyat bisa mendapatkan tunjangan rumah Rp50 juta, sementara dirinya belum punya tempat berteduh. Ia memikirkan anak-anaknya yang harus tidur di trotoar, dengan kebutuhan sehari-hari tak pernah terpenuhi.
Rohmah sudah tidak lagi berharap banyak dari para pejabat. Selama ini, ia tidak pernah merasakan kehadiran mereka. Keluarganya harus bertahan tanpa uluran tangan pemerintah.
Baginya, pemerintah memang tak pernah memerhatikan rakyat. Beberapa kali mobil pejabat lewat, namun tak pernah berhenti. Suatu waktu, ia pernah mendekati mobil presiden untuk menceritakan kondisi warga, tapi pasukan pengamanan menghalanginya. Rohmah sebenarnya marah dan kecewa dengan situasi saat ini, namun tak tahu harus berbuat apa.
“Suara rakyat kecil memang tidak pernah didengar,” ujarnya.
Alih-alih berharap pada pemerintah, Rohmah memilih fokus membesarkan anak-anaknya dengan pendidikan terbaik. Ia tak ingin dua anaknya yang masih sekolah berakhir seperti saudaranya yang berhenti karena terbentur biaya. Keinginannya satu: memutus rantai kemiskinan keluarga. Ia belum pernah merasakan sekadar hidup layak, di mana jalanan dan barang bekas sebagai teman seumur hidupnya.
***
Pukul setengah lima subuh, alarm ponsel Raul memecah kesunyian. Bunyi itu bukan hanya tanda salat, tapi juga sinyal untuk bersiap ke sekolah.
Raul bangun dari tempat tidur, membersihkan diri, dan mengenakan seragam Korpri. Ia menuju tempatnya mengajar, sebuah sekolah dasar di Kecamatan Gedongtataan, Pesawaran.
Raul telah mengajar beberapa tahun. Ia tahu betul rutinitas harian seorang guru. Sebelum sekolah negeri, dirinya pernah bekerja di sekolah swasta.
Di sekolah, Raul mengemban tugas sebagai wali kelas. Ia menghabiskan 2-3 jam setiap hari di dalam kelas, lima hari dalam seminggu. Namun, yang paling membuatnya khawatir adalah upah Rp450 ribu per bulan, dirapel tiga bulan sekali.
“Enggak cukup untuk makan,” katanya.
Raul berjalan ke ruang kelas, membawa beban pikiran. Pendapatannya setiap triwulan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ia masih bergantung pada bantuan orang tua.
Di tengah keadaan itu, kabar soal pemotongan upah honorer membuat Raul kias cemas. Perubahan alokasi dana bantuan operasional satuan pendidikan memperkecil harapannya. Sebelumnya, honor guru dan tenaga kependidikan honorer bisa diambil maksimal 50 persen dari bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP). Kini, alokasinya hanya 20 persen untuk tenaga nonaparatur sipil negara (ASN) di sekolah negeri dan 40 persen di sekolah swasta.
“Berat rasanya, tapi kalau sudah aturannya harus dipotong, mau bagaimana lagi,” ujarnya.
Saat ini, Raul hanya berharap diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Upah yang lebih manusiawi menjadi impian baginya, setelah bertahun-tahun hidup dengan gaji tak sepadan.
Di Bandar Lampung, Ani menghadapi persoalan serupa. Guru madrasah ibtidaiah itu menerima upah yang terbilang kecil, Rp387.500 per bulan. Penghasilan tersebut jauh dari kata layak, sehingga Ani harus memikirkan bagaimana mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Kondisi demikian memaksanya mencari pekerjaan tambahan. Setiap hari, Ani bekerja tanpa henti: mengajar di madrasah pada siang hari, mengisi materi bimbel sampai sore, dan memberi les privat pada malam hari.
“Praktis, saya tidak memiliki waktu istirahat. Itu pun masih belum cukup bertahan hidup di tengah harga bahan pokok yang melambung,” kata Ani.

Guru honorer juga menghadapi masalah lain, yaitu beban kerja ganda. Selain mengajar, mereka harus menangani tugas administrasi. Ini menguras waktu dan energi, sehingga mengurangi fokus utama sebagai pendidik.
Seperti Raul, Ani meminta pemerintah lebih peka dan mempertimbangkan kembali upah pekerja honorer. Ia ingin pemerintah memprioritaskan pengajar, bukan hanya pejabat yang jauh dari kenyataan.
“Tapi, sepertinya sulit dapat kebijakan yang adil. Sebaliknya, guru disebut beban negara, minim apresiasi dan pengakuan atas dedikasi,” ujarnya.
Situasi lebih buruk dialami sejumlah guru honorer di Kabupaten Way Kanan. Tri, bagian administrasi di salah satu SD, menggambarkan betapa sulitnya kehidupan guru honorer.
“Di sini, guru honorer hanya dibayar Rp18 ribu per jam,” katanya.
Namun, bayaran itu hanya berlaku untuk minggu pertama dalam satu bulan. Tiga minggu lainnya, mereka tidak mendapat bayaran apa pun. Seorang guru yang mengajar 8-16 jam per minggu, atau 32-64 jam kerja per bulan, semestinya mendapat Rp576.000-Rp1.150.000. Namun, kenyataannya, mereka hanya menerima Rp144.000-Rp288.000 per bulan, setara dengan bayaran 8-16 jam saja.
Guru dengan upah Rp144 ribu itu telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya untuk mengajar. Tiga dekade telah berlalu, dan ia telah membagikan ilmunya kepada ribuan anak. Namun, hingga saat ini, ia masih belum diangkat menjadi ASN. Kegagalan dalam seleksi PPPK yang dinilai dari hasil tes berbasis komputer, bukan masa pengabdian, membuatnya merasa tak dihargai.
Sekarang, perempuan paruh baya itu menjelang masa pensiun. Sepanjang hidupnya sebagai pendidik, ia tidak pernah menerima upah layak. Keadaan kian buruk dengan pengurangan alokasi dana BOSP untuk tenaga honorer.
Tri khawatir. Jika kondisi ini berlanjut, profesi guru tidak akan menarik bagi banyak orang. Ilusi sebagai pahlawan tanpa tanda jasa hanya membuat mereka menanggung beban berat.
Naiknya pendapatan anggota DPR hingga Rp104 juta per bulan seperti pukulan. Disparitas yang mencolok antara penghasilan keduanya membuat pertanyaan besar tentang keadilan. Jika dihitung secara kasar, penghasilan 580 wakil rakyat setara dengan upah lebih dari 201.000 guru honorer. Ini ironi, di mana dedikasi dan pengorbanan guru honorer tidak dihargai secara layak.
Kenaikan pendapatan legislator membuat para guru honorer merasa kecewa dan marah. Di tengah efisiensi anggaran, upah guru yang sangat kecil, dan kondisi ekonomi rakyat makin sulit, kenaikan penghasilan itu seperti pil pahit. Apalagi, banyak produk legislasi menuai protes.
“Gaji DPR berasal dari pajak rakyat, namun yang membayar pajak mendapat gaji tak layak,” ucap Tri.
***
Dua pekan setelah Agus Sulistiyo menanam bibit terong, gulma mulai muncul. Ia tahu bahwa rumput pengganggu itu bisa merebut air, nutrisi, dan cahaya matahari. Agus segera mengambil tindakan. Ia membersihkan gulma dengan telaten, memastikan bahwa terong tumbuh dengan baik.
Sebagai petani padi di Desa Gadingrejo, Pringsewu, Agus sehari-hari menggarap lahan seluas setengah hektare. Hasil panen dibagi dua dengan empunya lahan.

Untuk menambah pemasukan, Agus menanam terong di samping tanaman padi. Ia tahu bahwa pengelolaan terong relatif mudah. Masa panen juga lebih cepat ketimbang padi. Selain itu, terong tidak membutuhkan air sebanyak padi. Sehingga, sangat memungkinkan dijalankan pada kondisi minim air, seperti di daerahnya.
Rata-rata, petani penggarap di Gadingrejo punya pekerjaan tambahan. Ada yang menjadi kuli bangunan, sopir, atau berdagang. Langkah itu agar dapat mencukupi kebutuhan harian keluarga. Sebab, pendapatan petani hanya Rp600-Rp900 ribu per bulan. Itu pun bisa dinikmati setelah 3-4 bulan masa tanam. Artinya, selama padi belum panen, mereka harus memutar otak untuk bertahan hidup.
Kondisi itu diperparah oleh kenyataan bahwa kenaikan harga beras tidak serta-merta mengangkat perekonomian petani. Di tingkat petani, harga gabah tetap rendah, bahkan ketika harga beras melonjak.
Dalam waktu dekat, Agus akan memulai panen raya. Masalah lumrah yang dihadapi adalah penurunan harga gabah akibat stok meningkat. Dalam situasi ini petani hanya bisa pasrah. Mereka tak berdaya dalam menentukan harga jual. Mekanisme pasar yang dimonopoli pemilik modal menempatkan petani tidak punya kontrol atas keringatnya. Posisi mereka paling bawah dalam rantai produksi-disribusi padi.

Kondisi demikian sudah dirasakan Jariyah sepanjang hidupnya. Petani seperti dirinya muskil bisa keluar dari jurang kemiskinan. Mereka hanya menerima sebagian kecil dari hasil panen, sementara risikonya sangat besar. Jariyah menanggung beban kala gagal panen, tapi ketika harga beras tinggi, pendapatannya tak meningkat.
Berbeda dengan Agus yang masih kuat bekerja sampingan, Jariyah tidak bisa bekerja terlalu berat. Ia hanya bergantung hidup dari hasil panen padi.
“Kadang tidak cukup untuk kebutuhan, hanya bisa makan,” kata Jariyah dengan suara datar.
Situasi itu memaksa Jariyah terus berjuang. Panen yang sedikit dipakainya untuk konsumsi sendiri. Namun, kebutuhan yang mendesak sering kali memaksanya menjual gabah. Belum sampai panen selanjutnya, gabah sudah habis. Akibatnya, Jariyah harus membeli beras dengan harga relatif mahal.
Harga beras mencapai Rp14-Rp16 ribu per kg, sementara gabah yang dijualnya hanya Rp6.000-Rp7.000 per kg. Perbedaan harga yang sangat besar ini memaksanya berutang kepada tengkulak ketika paceklik. Pinjaman itu memiliki konsekuensi: Jariyah harus menjual hasil panen dengan harga murah.
Di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi Agus dan Jariyah, berita tentang kenaikan penghasilan anggota DPR terdengar seperti lelucon. Keduanya hanya geleng-geleng kepala. Total pendapatan seorang wakil rakyat per bulan setara dengan penghasilan petani dari 28 kali musim tanam padi, atau sembilan tahun.
Sebenarnya, Agus dan Jariyah sudah tak peduli dengan tindak tanduk pembuat undang-undang. Mereka melihat parlemen tak pernah mewakili suara rakyat.
“Datang kalau butuh suara saja. Hilang ketika terpilih.”
***
“Sapi Perah”
Kenaikan tunjangan anggota DPR mencuat setelah terbit Surat Sekretariat Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024. Setiap legislator berhak atas tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan. Jadi, total pendapatan bulanan mereka lebih dari Rp104 juta. Angka fantastis ini termasuk tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, tunjangan jabatan, bantuan listrik dan telepon, serta tunjangan beras.
Dengan jumlah anggota sebanyak 580 orang, negara harus mengeluarkan sekitar Rp29 miliar per bulan hanya untuk membiayai tunjangan rumah. Besaran itu setara Rp1,74 triliun selama satu periode masa jabatan. Ini adalah angka mengerikan, mengingat banyak kebutuhan lebih mendesak yang harus dipenuhi negara.
Kenaikan pendapatan wakil rakyat di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah memangkas dana pendidikan dan kesehatan yang berdampak pada kualitas pelayanan publik. Sementara itu, masyarakat dihadapkan kenaikan tarif PBB-P2 yang mencapai 250 persen, bahkan 1.000 persen di beberapa daerah. Kebijakan ini disebut dampak efisiensi, namun yang jelas adalah beban hidup masyarakat kian berat.
Gemuknya penghasilan anggota DPR juga bersamaan dengan pelonjakan harga barang pokok, gelombang PHK, angka pengangguran, dan tingkat kemiskinan ekstrem. Ekonomi masyarakat semakin merosot, daya beli menurun, dan pasar-pasar tradisional semakin sepi. Masyarakat tercekik oleh kebijakan yang tidak adil, sementara tanah-tanah warga direbut atas nama pembangunan dan investasi.
Dodi Faedlulloh, peneliti Laboratorium Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Lampung, menilai kenaikan tunjangan DPR di tengah kesulitan ekonomi rakyat telah menciptakan jurang yang dalam antara realitas sosial dan sensitivitas elite politik. Dalam perspektif kebijakan publik, keputusan terkait remunerasi pejabat negara semestinya didasarkan pada tiga prinsip: proporsionalitas, akuntabilitas, dan legitimasi sosial.
Namun, besaran tunjangan perumahan yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan terkesan seperti ejekan bagi guru honorer, tenaga kesehatan, dan pekerja informal yang berjuang untuk menopang pelayanan dasar masyarakat. Ini mengafirmasi kesenjangan struktural yang semakin memperlebar jurang ketidakadilan.

Lalu, soal akuntabilitas. Upah publik figur seperti wakil rakyat seyogianya berbanding lurus dengan kinerja. Namun, realitas menunjukkan parlemen justru banyak melahirkan kebijakan kontroversial, seperti UU Cipta Kerja atau KUHP, yang memicu gelombang protes. Dalam konteks ini, kenaikan penghasilan tampak lebih sebagai hadiah untuk kepentingan politik ketimbang penghargaan atas kinerja yang nyata.
Ihwal legitimasi sosial, kebijakan kenaikan pendapatan anggota legislatif tak pernah melalui proses konsultasi publik. Padahal, legitimasi politik hanya mungkin terjaga bila rakyat merasa diperlakukan adil dan dihargai. Tanpa itu, yang muncul adalah delegitimasi, ketidakpercayaan, dan semakin jauhnya jarak antara wakil rakyat dengan konstituennya.
Peningkatan penghasilan legislator tatkala rakyat menanggung beban ekonomi berat memperlihatkan kebijakan lebih condong pada kepentingan elite dibanding mandat kerakyatan. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi semakin terkikis.
Penulis buku “Birokrasi dalam Perspektif Kiri” itu melihat fenomena penambahan pendapatan anggota DPR merupakan manifestasi ketimpangan dalam logika bernegara yang semakin akut. Di satu sisi, rakyat terus dibebani dengan kenaikan pajak, efisiensi anggaran daerah yang mengancam layanan dasar, dan perampasan ruang hidup atas nama pembangunan. Sementara, wakil rakyat menikmati fasilitas dan tunjangan yang mewah.
Dalam perspektif ekonomi politik, negara menghadapi tekanan untuk membiayai program-program politik yang tidak berbasis pada data dan kebutuhan rakyat, melainkan kepentingan elite. Sumber daya yang diekstraksi dari rakyat melalui pajak dan penghematan layanan publik justru digunakan untuk menopang kenyamanan elite. Efisiensi tidak diarahkan untuk memangkas privilese pejabat, melainkan mengurangi pelayanan publik yang paling dirasakan rakyat. Negara tampil bukan sebagai pelindung kepentingan publik, tapi predator yang menjadikan rakyat sebagai sumber rente untuk menopang kekuasaan dan kemakmuran elite.
“Jadi, wajar kalau rakyat merasakan posisinya seperti ‘sapi perah’, yang hanya diperas untuk kepentingan segelintir orang,” kata Dodi.
Ia memandang pembentuk undang-undang bukan sekadar tidak peka terhadap aspirasi rakyat. Dalam perspektif state capture, DPR dapat dilihat sebagai bagian dari elite predatoris yang menggunakan kekuasaan formal untuk merampas hak-hak publik secara sistematis. Mereka beroperasi dalam kerangka demokrasi elektoral yang tampak sah, namun praktiknya menyerupai kekerasan struktural yang dilembagakan melalui kebijakan dan anggaran, sehingga merugikan masyarakat secara luas dan terus-menerus.
Dengan demikian, mereka bisa disebut sebagai aktor predator politik yang memanfaatkan posisi struktural untuk mengekstraksi sumber daya publik dan memindahkannya ke kantong-kantong kekuasaan. Ini menandakan bahwa demokrasi Indonesia telah bergeser ke arah demokrasi delegatif yang hanya memenuhi prosedur formal, tetapi secara substantif melanggengkan praktik oligarki dan ketidakadilan.
Kekuasaan Berganti, Sistem Tak Berubah
Untuk memahami anomali yang terjadi, termasuk paradoks kenaikan penghasilan anggota DPR, demografer politik Riwanto Tirtosudarmo mengajak masyarakat melihat persoalan tersebut dari perspektif sejarah. Menurutnya, apa yang dilakukan parlemen bukanlah satu problem tunggal dan masalah baru, melainkan sebuah gejala sosial yang mengakar dari penyakit kronis penguasa di negeri ini: keterkungkungan pada logika kapitalisme.
Sepanjang 80 tahun Indonesia merdeka, rezim yang berkuasa selalu terbelenggu oleh kepentingan ekonomi yang sempit, tanpa memikirkan nasib orang banyak. Logika kekuasaan hanya bersandar pada akumulasi kapital dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia, sehingga memperlebar kesenjangan sosial.
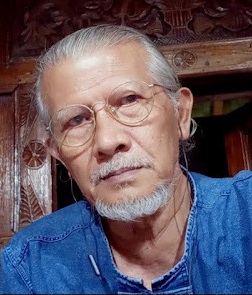
Dari masa ke masa, mulai demokrasi terpimpin hingga reformasi, kekuasaan hanya berganti wajah. Sistem yang dijalankan tetap sama: sekelompok kecil individu memegang kendali atas kekuasaan politik dan ekonomi. Demokrasi yang seharusnya menjadi alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, justru menjadi kedok melegitimasi kekuasaan oligarki.
Rakyat hanya dinantikan kehadirannya ketika merayakan bentuk-bentuk demokrasi procedural, seperti pemilihan umum. Selepas itu, suara rakyat tidak pernah lagi didengar. Mereka hanya menjadi penonton pasif dalam permainan kekuasaan yang dimainkan oleh para elite.
“Jadi, Indonesia tidak pernah benar-benar menjalankan demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Semuanya berdasar kepentingan para oligark,” ujarnya.
Beberapa tahun kemudian, UU Penanaman Modal Asing menjadi titik balik perjalanan Indonesia menuju neoliberalisme. Cukong-cukong semakin berkuasa, dengan modal asing mengalir deras. Mereka bekerja sama dengan investor asing, tanpa ada kekuatan progresif yang mampu menentang. Hasilnya, “Hingga hari ini negara tersandera para pemilik modal.”
Untuk mengubah keadaan harus memulai dari bawah. Kelas menengah yang menjadi motor gerakan kembali ke basis, membentuk dan membangun literasi politik melalui diskursus kecil di kelompok-kelompok masyarakat. Lewat ruang itu, warga dapat membicarakan persoalan-persoalan mendasar dan secara perlahan mengubah cara pandang sebuah problem.
Mereka akan menyadari bahwa penindasan dan ketidakadilan bukanlah masalah tunggal, melainkan bentuk kejahatan struktural yang memerlukan perubahan sistemik. Dengan menyadari persoalan kronis itu secara holistik, masyarakat dapat mengambil langkah tepat. Bukan hanya melawan individu-individu culas, tapi juga sistem penghambaan kapital yang menyengsarakan rakyat.
“Penindasan dan kesewenang-wenangan akan terus terjadi bila akar masalah tidak tercabut,” kata Riwanto.(*)
Laporan Derri Nugraha
Liputan ini mendapat dukungan dari Yayasan Kurawal sebagai upaya memperkuat demokrasi.









