Indonesia merupakan bangsa yang lahir melalui revolusi. Sebagai sebuah bangsa, tujuan besar yang hendak dicapai adalah demokrasi. Tetapi, akhir-akhir ini, kehidupan bersama sedang diuji: politik yang makin elitis, ekonomi dimonopoli para oligark, dan kian jauhnya keadilan sosial.
Riwanto Tirtosudarmo | Bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak 1980-2017 | Kini Peneliti Independen
Ada dua buku tentang kelahiran Indonesia yang terbit hampir bersamaan pada 2024. Buku pertama, Merdeka: The Struggle for Indonesian Independence and the Republic’s Precarious Rise 1945–1950, ditulis oleh Harry Poeze ((lahir 1947) dan Henk Schulte Nordholt (lahir 1953). Buku kedua berjudul Revolusi: Indonesia and the Birth of the Modern World, karya David Van Reybrouck (lahir 1971).
Seperti buku pertama, buku kedua meskipun penulisnya seorang jurnalis kewarganegaraan Belgia; aslinya ditulis dalam Bahasa Belanda. Penulis buku pertama, Harry Poeze adalah sejarawan dan Henk Schulte Nordholt, antropolog yang sering menyebut juga sebagai sejarawan; kedua nama ini sudah tidak asing lagi di Indonesia.
Penerjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Inggris memperlihatkan berkuasanya bahasa Inggris sebagai bahasa akademik maupun bahasa sastra di dunia internasional. Kedua buku ini, saya katakan, sebagai kisah kelahiran Indonesia karena secara kebetulan (saya kira) keduanya mengupas sejarah Indonesia dalam periode yang kurang lebih, sampai dengan tahun 1950.
Dalam kedua buku itu sejarah panjang kolonialisme Belanda diuraikan dengan rinci tanpa sikap harus membela diri (sebagai orang Belanda atau orang Belgia) ataupun menghakimi. Yang menarik bagi saya adalah ketika menguraikan sejarah sekitar proklamasi dan tahun-tahun pertama setelahnya, hingga diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada 1949. Pilihan kata “Merdeka” pada judul buku pertama, dan kata “Revolusi” pada judul buku kedua, mencerminkan simpati mereka kepada Indonesia
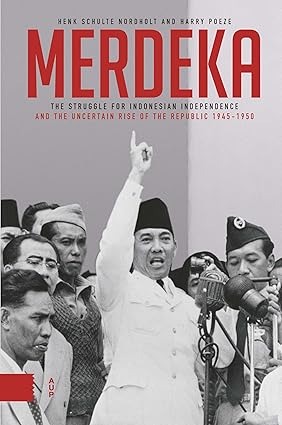
Buku “Merdeka” dimulai dengan kutipan dari tulisan Taufik Abdullah yang menyentuh. Pembicaraan terakhir antara Hatta dan Soekarno yang terbaring sakit. “They held each other’s hands. They didn’t need to say much to each other because they know: ‘We did it!’. Kalimat itu dikutip dari buku Taufik Abdullah, yang menurut saya, sangat penting.
Buku tebal itu berjudul ringkas Indonesia Towards Democracy, diterbitkan ISEAS tahun 2009. Buku karya “magnum opus” Taufik Abdullah (lahir 1936), sejarawan senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) – menarik disandingkan dengan kedua buku yang mengisahkan kelahiran Indonesia di atas. Mengapa? Karena Taufik Abdullah yang menerbitkan bukunya tahun 2009 menghela kita pada sebuah optimisme sebagai bangsa yang lahir melalui revolusi yang melahirkan kemerdekaan, sebagaimana secara simpatik dituturkan oleh para penulis dua buku pertama tadi. “Demokrasi” yang menjadi kata kunci dalam judul buku Taufik Abdullah, adalah tujuan yang ingin dicapai Indonesia setelah melalui sejarah panjangnya melalui berbagai zaman itu.
Jika Taufik Abdullah, menulis sejarah Indonesia “from within”, para penulis buku pertama dan kedua boleh dikatakan menulis dari luar. Tapi, apakah ada bedanya menulis dari dalam dan dari luar, ketika keduanya dilandasi oleh empati dan respek terhadap subjek yang ditulisnya? Membaca ketiga buku ini, “Revolusi”, “Merdeka”, dan “Demokrasi”, saya merasakan bahwa menjadi warga bangsa Indonesia adalah sebuah kebanggaan. Ada sense of belonging dari sebuah komunitas yang terhormat. Perasaan ini menguat, terutama akhir-akhir ini ketika ke-Indonesia-an seperti kembali didera oleh ketidakpastian, kehidupan bersama yang sedang diuji oleh politik yang semakin elitis, ekonomi yang dimonopoli oleh para oligark dan keadilan sosial yang semakin menjauh bagi orang banyak. Para pemimpin Indonesia hari ini yang tenggelam dalam kubangan kepentingan jangka pendek – tak lagi ingat ketika para pejuang kemerdekaan mempertaruhkan nyawanya dan ketika revolusi sudah dianggap telah mati, masihkah mereka kita anggap sebagai pemimpin?
Para penulis buku di atas, Harry Poeze and Henk Schulte Nordholt, David Van Reybrouck dan Taufik Abdullah telah menorehkan tinta untuk menulis dengan indah kelahiran bangsa Indonesia yang dicapai melalui revolusi perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme; dan ketika reformasi dimulai pascarepresi Orde Baru; ada harapan Indonesia akan menuju masyarakat yang lebih demokratis. Tapi, jangan-jangan kita kembali ke kondisi bangsa Indonesia seperti digambarkan oleh penulis buku pertama dan kedua, ketika pada tahun 50-an memasuki zaman yang serba tidak pasti.

Karena itu, menarik jika buku pertama dan kedua berhenti pada 1950. Tahun 50-an yang semula digambarkan penuh harapan dengan Pemilihan Umum 1955 yang demokratis, kemudian mulai memasuki masa-masa penuh ketegangan, pemberontakan daerah, dan Presiden Soekarno membubarkan sidang konstituante yang sedang menyusun UUD baru melalui Dekrit 1959, lalu menyatakan kembali ke UUD 1945. Sejarawan muda cemerlang dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Farabi Fakih (lahir 1981) menulis disertasi yang menarik tentang periode ini. Disertasi di Universitas Leiden itu kemudian dibukukan (2020) dengan judul Authoritarian Modernization in Indonesia’s Early Independence Period: The Foundation of the New Order State (1950–1965). Saat ini, seperempat abad setelah berakhirnya Orde Baru 1998, tampaknya kita memasuki periode otoritarianisme kembali. Apakah ini membenarkan kata orang pintar bahwa sejarah berulang?
Buku “Merdeka” aslinya ditulis dalam bahasa Belanda, terbit tahun 2022, sementara terjemahan Inggrisnya terbit pada 2024. Buku ini bisa dibilang ditulis untuk publik Belanda dan karena mungkin ada semacam ironi sebagai orang Belanda yang melihat sejarahnya sendiri. Sebagai koloni terbesar Belanda, dan kemudian berhasil merdeka, pasti mempunyai tempat tersendiri dalam benak publik Belanda, terutama untuk generasi tuanya. Untuk generasi muda? Mungkin sama di Belanda dan di Indonesia, tidak terlalu peduli, kecuali segelintir yang memang meminati sejarah.
Harry Poeze dan Henk Schulte Nordholt adalah dua akademisi Belanda yang mendedikasikan dirinya untuk meneliti sejarah dan masyarakat Indonesia. Sebelum menulis buku ini, mereka telah menerbitkan banyak buku tentang Indonesia. Harry Poeze, misalnya, telah menulis lima jilid buku tentang Tan Malaka. Henk Schulte Nordholt, selain meneliti juga menjadi pembimbing tidak sedikit mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda, khususnya di Universitas Leiden. Oleh karena itu, tak mengherankan jika buku “Merdeka” ditulis dengan informasi dari arsip sangat lengkap yang banyak tersimpan di Belanda, terutama di KITLV.
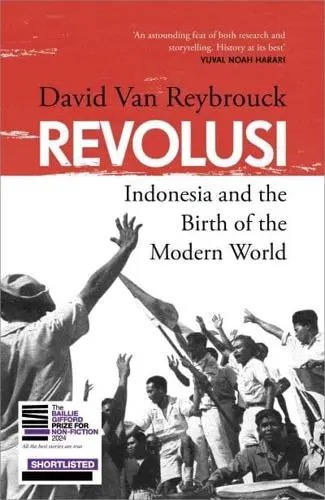
Sementara itu, buku”Revolusi” ditulis oleh seorang jurnalis Belgia yang membaca biografi singkatnya memiliki reputasi menulis buku, naskah drama dan novel; yang memperoleh banyak penghargaan dan pujian. Sebelum menulis tentang Indonesia, bukunya tentang Kongo, negeri di Afrika bekas jajahan Belgia: Congo: The Epic History of a People telah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Dalam menulis buku “Revolusi”, David Van Reybrouck membutuhkan waktu lima tahun untuk menyelesaikannya. Buku yang aslinya ditulis dalam bahasa Belanda ini, seperti buku “Merdeka” kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Adakah yang hilang dalam alih bahasa ini (lost in translation)? Mungkin saja ada, tetapi dugaan saya alih bahasa itu telah dilakukan dengan sangat baik dan terjaga kualitas dan rasa bahasanya.
Membaca kedua buku ini, segera terasa genre penulisan yang sangat berbeda antara karya akademisi dan karya jurnalis yang menulis dengan gaya sastrawi. Selain menggunakan arsip, David Van Reybrouck juga melakukan kunjungan ke berbagai tempat di Indonesia seperti Lombok, Ternate dan Pare di Jawa Timur; tentu selain kota-kota besar seperti Jakarta Bandung dan Yogyakarta. Mewawancarai banyak orang Indonesia secara mendalam; selain juga wawancara dengan banyak narasumber di Belanda dan Belgia. Dalam epilog bukunya, David Van Reybrouck menarasikan kisah-kisah para narasumbernya dengan kata-kata mereka langsung, sehingga terasa sangat hidup. Di sana kita bisa merasakan empatinya yang dalam dari manusia-manusia yang mengalami secara langsung pasang surut sejarah bangsanya.
Taufik Abdullah adalah sejarawan yang terkenal dengan gaya penulisannya yang juga sangat hidup. Esai-esai yang ditulisnya sangat puitis, salah satu yang saya suka adalah esainya untuk buku 70 Tahun koleganya dari Aceh yang menjadi kakak kelasnya di Jurusan Sejarah Universitas Gajah Mada, Ibrahim Alfian. Judul esainya singkat, “Wijilan”. Bagi akademisi di Yogyakarta, terutama generasi tuanya, Wijilan adalah nama sebuah tempat dahulu mereka kuliah sebelum UGM memiliki gedung yang mahamegah, seperti sekarang. Dalam esainya itu Taufik Abdullah mengambarkan dengan liris kehidupannya bersama Ibrahim Alfian sebagai “wong sabrang” dan pengalamannya mengikuti kuliah dari dosen-dosen sepuh, seperti Profesor Purbatjaraka dan rekan-rekannya dari Belanda.
Magnum Opus-nya Indonesia: Towards Democracy, terbit tahun 2009 ketika harapan akan masa depan demokrasi di Indonesia tampak bersinar. Saat itu, sekitar 10 tahun dari apa yang dalam bab terakhir (bab 6) bukunya dideskripsikannya sebagai berakhirnya sebuah rezim yang disebutnya sebagai Greedy State (Negara Rakus). Buku yang terdiri enam bab di luar pengantar dari Wang Gungwu dan epilog ini, lumayan tebal, hampir 700 halaman. Buku ini adalah hasil dari sebuah proyek penulisan tentang “nation building” di Asia Tenggara yang dipimpin oleh Profesor emeritus dari National University of Singapore (NUS) Wang Gungwu (lahir di Surabaya 1930), ahli sejarah yang saat ini barangkali paling senior di Asia Tenggara. Sebagai sejarah nasional, maka bab-bab dalam buku ini melihat lintasan sejarah Indonesia dalam sapuan kanvas besar.
Dalam paragraph terakhir epilognya, terbaca optimisme Taufik Abdulah: If history has any lesson to give, then one can also see that it is the creative understanding of the present and the past and the willingness to visualize a brighter future that has successfully planted the seeds of the new nation called Indonesia. Now, after Indonesia has passed through all kinds of social and political experiences — some, quite promising, while others very disappointing — it has grown into an adult nation that may still make mistakes, but in the process, it also gained some wisdom. In time to come, Indonesia may again recover its almost forgotten creative responses to new and unprecedented challenges (halaman 570).
Melihat apa yang terjadi selama dasawsarsa terakhir ini, jika harus menulis lagi, Taufik Abdullah, barangkali tidak akan seoptimis itu.(*)
Esai ini menghormati Taufik Abdullah yang akan berulang tahun ke-89 pada 3 Januari 2025.









