Politik transaksional yang mengabaikan etika dan nilai-nilai demokrasi menandai perjalanan rezim Jokowi. Kebijakan-kebijakan tidak populer, seperti Food Estate dan UU Cipta Kerja, memperlihatkan rupa kekuasaan yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi ketimbang kepentingan orang banyak. Pengalaman ini mengajarkan akan pentingnya membangun gerakan rakyat secara terorganisasi.
Pendar temaram memenuhi Kafe Nuwono Tasya pada Jumat malam, 8 Agustus 2025. Sejumlah kalangan dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, jurnalis, aktivis, seniman, pegiat literasi, dan mahasiswa, berkumpul. Mereka duduk melingkar, menanti diskusi bersama Riwanto Tirtosudarmo, demografer politik pertama di Indonesia. Bangunan kafe dengan arsitektur klasik menjadi latar belakang untuk perbincangan yang hangat.
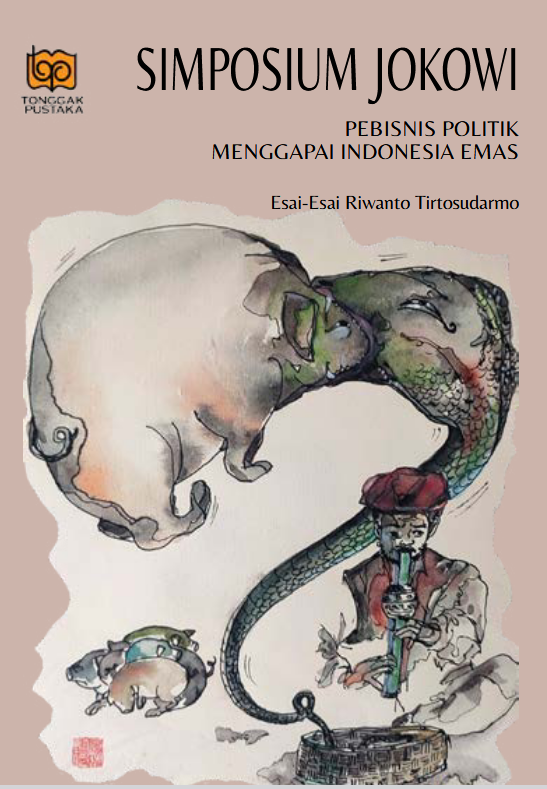
Riwanto bertandang ke Lampung guna bertukar pikiran soal bukunya “Simposium Jokowi: Pebisnis Politik Menggapai Indonesia Emas.” Buku itu mendedahkan pandangannya mengenai dinamika sosial-politik kontemporer.
Riwanto menghabiskan masa kecil di Tegal, Jawa Tengah. Lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, ia bekerja sebagai peneliti sosial di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) hampir empat dekade.
Pendiri Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) itu menempuh pendidikan S-2 dan S-3 di bidang demografi-sosial di Australia. Pengalaman internasionalnya juga mencakup undangan sebagai peneliti tamu di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Jepang, dan Singapura.
Membaca dan menulis adalah nyawa bagi Riwanto. Sejak mahasiswa sampai sekarang, ia telah menghasilkan banyak tulisan ilmiah dalam bentuk buku dan jurnal. Pada masa Pandemi Covid-19, Riwanto mulai terbiasa menulis esai. Kumpulan artikelnya telah diterbitkan berseri dalam lima buku bertajuk “Mencari Indonesia”, yang menjadi cerminan dari keresahan dan kegelisahannya tentang keadaan sosial-politik di Indonesia.
Riwanto pun tertarik merangkai puisi. Beberapa kumpulan puisinya yang telah diterbitkan, seperti Secangkir Kopi di Pagi Hari (Kampung Limasan Tonjong, 2023), Di Galeri Sumbing (Media Nusa Creative, 2024), Mencari Revolusi (Tonggak Pustaka, 2024), dan dalam proses kumpulan keempat, Lorong Waktu (Tonggak Pustaka, 2025).
Kembali pada “Simposium Jokowi”, buku itu berisi 10 esai Riwanto yang dimuat konsentris.id secara serial, November 2023-Januari 2024. Melalui tulisan-tulisannya, Riwanto berupaya menyingkap realitas di balik tindak tanduk kekuasaan.
Esai-esai Riwanto berpusat pada Jokowi. Selama satu dekade menjadi Kepala Negara, Jokowi memiliki pengaruh besar atas dinamika sosial-politik di Tanah Air. Lewat catatan kecilnya itu, Riwanto mencermati perilaku, menggambarkan pola, dan mengungkap motif-motif di balik perangai penguasa.
Ia memaparkan kemungkinan-kemungkinan dampaknya bagi kehidupan publik dan generasi mendatang. Meski tidak terlalu mendalam, Riwanto berharap esai-esai tersebut bisa menjadi bahan pembelajaran bersama untuk mengubah keadaan lebih baik.
Matinya Etis Politik
Dalam persamuhan yang berlangsung hingga tengah malam, muncul bermacam pandangan ihwal kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Fuad Abdulgani, seorang sosiolog, memulai dialektika dengan mengajukan tesis: masa pemerintahan Jokowi sebagai bentuk nyata matinya etika dalam berpolitik. Dengan nada tegas, ia menyampaikan bahwa Jokowi beserta kroninya hanya memandang politik sebagai transaksi bisnis. Alhasil, segala keputusan politik hanya ditimbang dari kacamata bisnis yang menekankan soal untung-rugi daripada kepatutan.
10 tahun terakhir, diskursus soal ketatanegaraan absen dari dinamika politik nasional. Sebaliknya, yang mencuat adalah kepentingan segelintir golongan tanpa memikirkan rakyat. Fenomena itu terlihat dalam berbagai keputusan dan produk kebijakan, di mana aturan yang mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya menjadi prioritas, kendati merampas hak rakyat, merusak alam, dan mengeruk sumber daya.
Fuad mencontohkannya melalui riset soal Food Estate, proyek yang diklaim sebagai upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Secara praktik, Food Estate dijalankan dengan skema pertanian kontrak. Pola ini menghubungkan petani kecil berbasis tenaga kerja rumah tangga dengan kontraktor, menciptakan ikatan yang tidak seimbang antara kekuatan ekonomi dan kelemahan petani.
Kontraktor akan menginvestasikan input pertanian sesuai jenis yang dibutuhkan petani, seperti benih, pupuk, dan pestisida. Kala panen, petani wajib menjual kepada kontraktor. Dari hasil penjualan tersebut, petani harus membayar kembali pinjaman untuk input pertanian yang telah diterima sebelumnya. Sisa hasil penjualan setelah membayar pinjaman itulah yang menjadi keuntungan bersih petani.
Dalam studi kritis agraria, kondisi ini disebut ‘perampasan kuasa’ petani oleh korporasi. Mereka terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan dan kehilangan kontrol atas tanah dan hasil panen. Petani hidup dalam ketidakpastian, sementara korporasi terus meraup untung dari keringat dan darah mereka.
Selain itu, pelaksanaan Food Estate di banyak daerah dengan membabat jutaan hektare hutan, menghancurkan ekosistem lokal yang telah terawat selama berabad-abad, dan mengusir masyarakat adat dari tanah leluhur. Hutan hijau nan lebat, tempat berbagai spesies hidup dan berkembang, berubah menjadi lahan pertanian monokultur. Dalam kondisi tersebut, tentu yang dikedepankan adalah kepentingan ekonomi para pemilik modal ketimbang konservasi alam dan kemakmuran rakyat.
Kebijakan lainnya, pengesahan UU Cipta Kerja yang menjadi karpet merah bagi investor untuk invasi bisnis. Beleid yang membuka peluang investasi sebesar-besarnya itu semakin mengerdilkan hak-hak normatif pekerja, melanggengkan bisnis ekstraktif yang mengisap sumber daya alam, dan merampas tanah rakyat.
“Jadi, kebijaksanaan dan keutamaan dari negara itu sudah tak penting lagi. Yang ada hanya kepentingan bisnis,” kata Fuad.

Ia melihat, politik transaksional yang dijalankan rezim Jokowi telah menjadi rol model dalam dinamika politik. Banyak kepala daerah atau pejabat yang terpilih karena hubungan bisnis, jaringan keluarga, dan kepentingan golongan tertentu. Pemilihan tak lagi berdasarkan kompetensi dan dedikasi, melainkan relasi serta kepentingan politik.
Ruang publik hanya diramaikan oleh politik pencitraan dan penampilan, di mana rupa dan popularitas lebih penting ketimbang substansi dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Selain itu, Jokowi memberi banyak kewenangan TNI mengurus proyek-proyek sipil, bahkan sampai tahap implementasi, seperti ketahanan pangan.
Fuad menilai, langkah strategis politik Jokowi untuk mendapatkan dukungan militer terlihat dari sejarah peran penting militer dalam gejolak politik Indonesia. Pada masa Orde Baru, struktur militer sangat besar dan mengakar hingga ke lapisan bawah. Pengaruh militer menjadi salah satu yang diperhitungkan oleh penguasa.
Pendapat itu terafirmasi dalam kebijakan pemerintahan Prabowo. Presiden merekrut puluhan ribu prajurit dan membentuk Komando Daerah Mililiter baru serta Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di seluruh Indonesia.
Pernyataan Fuad ihwal hilangnya etika dalam berpolitik juga diulas dalam esai pertama Riwanto berjudul “Jokowi Pebisnis Politik“. Riwanto memandang, sebagai seorang pebisnis, Jokowi tak mengenal dan tidak menjalankan ideologi politik yang umum dalam dunia politik. Bagi pengusaha mebel itu, politik berubah menjadi bisnis yang hanya berorientasi keuntungan.
Sistem politik dirancang untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya. Memperlakukan politik sebagai bisnis berarti mencapai tujuan politik setinggi-tingginya dengan ongkos politik serendah-serendahnya. Politik kehilangan esensi dan nilai-nilainya. Hanya menjadi alat untuk mencapai kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Sebagai pebisnis, Jokowi mengalkulasi politik layaknya berdagang. Sifat ini terlihat jelas ketika ia merangkul mantan lawan politiknya dalam pemerintahan. Prabowo, rivalnya dalam pilpres, diangkat menjadi Menteri Pertahanan, sebuah langkah tak biasa dalam sejarah politik Indonesia.
Keputusan ini ternyata berbuah manis. Prabowo kemudian menggandeng Gibran Rakabuming, anak sulung Jokowi, sebagai Wakil Presiden – memungkinkan Jokowi tetap memiliki pengaruh meskipun tak lagi berkuasa.
Insting bisnis Jokowi juga terlihat saat ia memilih Profesor Ma’ruf Amin ketimbang Profesor Mahfud MD dalam Pilpres 2019. Perhitungannya adalah Ma’ruf dapat membantu melumpuhkan kelompok Islam garis keras yang berpotensi menghambat langkahnya menjadi presiden kedua kali.
Rezim Manipulatif
Hal lain yang menjadi perbincangan hangat adalah cerita Rin, seorang relawan Jokowi yang menyaksikan langsung perjalanan politik mantan presiden itu. Ia menyebut pemerintahan Jokowi sebagai manifestasi dari rezim manipulatif yang terstruktur dan sistematis. Citra Jokowi sebagai pemimpin merakyat dibentuk melalui manipulasi algoritma di berbagai kanal media elektronik, sehingga menciptakan persepsi positif di mata publik.
Pendukung Jokowi dengan cermat menyebarkan berbagai informasi dan narasi untuk membentuk pendapat umum. Mereka membangun konstruksi bahwa Jokowi adalah sosok yang peduli dengan masyarakat miskin dan membawa perubahan nyata. Hasilnya, citra Jokowi sebagai pemimpin yang merakyat semakin kuat dan melekat, bahkan menjadi bagian integral dari identitas politiknya.
Salah satu narasi yang didengungkan, yaitu “Jokowi adalah Kita.” Kampanye ini mengeksploitasi latar belakang Jokowi sebagai tukang kayu dan rakyat jelata untuk membangun citra pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Dengan memanfaatkan kesan sebagai orang biasa, Jokowi berusaha melawan stereotip penguasa dari kalangan elite.
“Bahkan, cara berjalan dan berpakaian pun di-setting supaya terlihat baik,” kata Rin, menggambarkan bagaimana hal detail diperhatikan untuk memperkuat citra positifnya.
Hasil dari kerja-kerja relawan itu luar biasa: popularitas Jokowi melejit drastis. Ia menjadi topik pembicaraan di berbagai ruang, baik di kota maupun desa. Branding-nya satu dan konsisten: pemimpin yang merakyat, harapan “wong cilik” atau rakyat kecil.
Kepopuleran Jokowi juga terlihat dalam pemberitaan media-media nasional dan internasional yang turut mengamplifikasi sosoknya. TIME menjadikan foto Jokowi sebagai sampul depan edisi 27 Oktober 2014.
Majalah terkemuka di Amerika Serikat itu menulis Jokowi sebagai harapan baru dan kekuatan bagi demokrasi. Jokowi akan memimpin Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, kekayaan alam melimpah, dan populasi muslim terbesar di planet ini.
Rin sepakat dengan Fuad dan Riwanto soal politik transaksional. Ia bilang, kerja-kerja manipulatif yang melibatkan para relawan tak lepas dari negosiasi kepentingan. Dalam konteks ini, Rin bersama penggiat desa rela membantu kampanye pencalonan Jokowi sebagai presiden. Syaratnya, Jokowi bersedia memuluskan kebijakan Rp1 miliar per desa.
Kesepakatan ini kemudian menjadi motor penggerak bagi para relawan. Mereka gencar mempromosikan Jokowi lewat berbagai ruang. Ketika Jokowi terpilih, kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan.
“Memang tidak ada etika politik, hanya ada kepentingan kekuasaan,” ujarnya.

Sejumlah peserta diskusi termangu mendengar cerita Rin. Mereka sebelumnya mengaku tersihir oleh citra Jokowi yang tampak sederhana dan dekat dengan rakyat. Bahkan, beberapa berterus terang sebagai pendukung Jokowi pada Pilpres 2014.
Gambaran Jokowi saat itu begitu kuat. Ia menjadi sosok dirindukan rakyat yang muak dengan oligarki dan dinasti politik. Jokowi berhasil menarik dukungan dari berbagai kelompok masyarakat sipil, mulai kaum liberal progresif, sosialis kiri, hingga fundamentalis.
“Mereka waktu itu yakin bahwa Jokowi adalah ‘Satria Piningit’ yang lahir sejak kemunculannya dalam politik. Tapi, ternyata rezimnya merusak demokrasi,” kata Amnesty Amalia Utami, aktivis Solidaritas Perempuan Sebay Lampung.
Sebenarnya, Amnesty sudah menyadari sifat manipulatif pemerintahan Jokowi. Ia melihat hal itu dari kebijakan-kebijakan yang baginya solusi palsu. Misal, janji pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan pekerja, termasuk buruh perempuan, melalui UU Cipta Kerja. Kenyataannya, langkah tersebut justru melegitimasi pasar bebas yang memudahkan kepentingan para pemodal, eksploitatif terhadap alam, dan politik upah murah buruh perempuan.
“Dengan mempermudah perizinan, hak-hak normatif pekerja dipangkas. PHK di mana-mana. Lapangan kerja semakin sulit. Perlindungan sosial bagi pekerja minim, sehingga dampaknya dirasakan berlapis oleh buruh perempuan,” ujarnya.
Sementara itu, nasib buruh rumah tangga semakin tidak jelas. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan Perlindungan Pekerja Migran yang diusulkan masyarakat sipil masih terkatung-katung. Pekerja rumah tangga maupun buruh migran terus berjuang tanpa perlindungan memadai.
Pada sisi lain, eksekutif dan legislatif dengan cepat mengesahkan kebijakan-kebijakan yang ditentang banyak orang, seperti revisi UU KPK, UU Minerba, UU TNI, dan KUHP. Minimnya perspektif perlindungan hak publik, termasuk perempuan dan lingkungan, menjadi salah satu penyebab eksploitasi tetap langgeng. Atas nama investasi dan pembangunan, masyarakat serta alam selalu menjadi korban.
Arah Gerakan Rakyat
Menjelang akhir diskusi, pandangan para peserta mengerucut pada lanskap politik kontemporer di Indonesia. Bayang-bayang Orde Baru masih menghantui, seolah-olah waktu tidak berlalu.
Haykal Rasyid, pegiat literasi jalanan, menyatakan bahwa lebih dari 27 tahun pascakeruntuhan rezim Orde Baru, apa yang dicita-citakan lewat agenda reformasi masih utopis. Masyarakat tetap terseret dalam peta politik Orde Baru, di mana pers dibungkam, kekerasan dan pelanggaran HAM di mana-mana, kriminalisasi, ketimpangan kepemilikan lahan, dan kesenjangan sosial.
Krisis kapitalisme global yang melanda satu dekade pemerintahan Jokowi memicu kebijakan semakin neoliberal. Pandemi Covid-19 melumpuhkan ekonomi global, perang dagang AS-Tiongkok menguat, dan ketidakstabilan ekonomi meluas. Logika pemerintahan pun terbentuk: investasi adalah obat mujarab untuk mengatasi krisis ekonomi. Segala cara ditempuh untuk mendatangkan investor, meski harus mengorbankan rakyat dan lingkungan.
Masyarakat terjebak dalam pusaran demokrasi prosedural, di mana pemilihan umum dan pelantikan wakil rakyat menjadi ritual kosong untuk mempertahankan dominasi modal. Haykal lalu mengajukan pertanyaan: ketika lembaga pengawal konstitusi justru membangkanginya, demokrasi dibunuh oleh mereka yang diangkat dari proses demokratis, dan kebijakan-kebijakan hanya mengakumulasi ketertindasan rakyat, ke mana arah gerakan masyarakat sipil?

Tidak ada jawaban tunggal atas pertanyaan Haykal. Masing-masing peserta diskusi memiliki interpretasi tersendiri. Riwanto berupaya menjawab dengan menekankan pentingnya mengorganisasi rakyat, sehingga basis-basis perlawanan dapat tumbuh dan mengakar.
Dodi Faedlulloh, akademisi Universitas Lampung, menawarkan perspektif berbeda. Menurutnya, perlawanan bisa muncul dari mana saja, termasuk gerakan rimpang yang sering dikritik lantaran spontan, episodik, dan tidak berstruktur. Banyak yang menilai gerakan ini tak memiliki arah jelas dalam menyerang struktur kekuasaan dan merebut ruang politik, sehingga kerap kali seremonial atau perayaan perlawanan.
Kendati demikian, gerakan rimpang merepresentasikan kemarahan yang masih menyala. Mereka adalah cermin bahwa kemarahan terhadap kekuasaan masih hidup, hanya belum menemukan saluran historisnya. Tugas selanjutnya adalah mengubah moralitas menjadi politik dan mengarahkan afeksi itu menjadi kekuatan kolektif yang terorganisasi.
Gerakan tersebut bisa menjadi gerbang untuk membangun organisasi rakyat yang tahan lama. Kemarahan rakyat yang menjalar melalui berbagai ruang, dari media sosial hingga protes jalanan, menunjukkan bahwa daya resistansi terhadap kekuasaan masih kuat dan menyebar. Namun, alih-alih hanya mengandalkan viralitas atau aksi reaktif, masyarakat perlu menciptakan struktur yang mampu menampung, mendidik, dan memobilisasi energi itu menjadi gerakan yang lebih terarah dan berjangka panjang.
“Di sinilah pentingnya membangun organisasi berbasis kelas yang tidak hanya responsif terhadap isu, tetapi juga menyusun strategi perubahan sosial secara sistemik,” kata Dodi.
Pernyataan itu menutup diskusi. Keheningan yang menyusul seakan menegaskan bahwa perjalanan panjang masih terbentang di depan. Akankah langkah kecil malam itu menjadi titik balik bagi perubahan yang lebih besar?
Laporan Derri Nugraha
Liputan ini mendapat dukungan dari Yayasan Kurawal sebagai upaya memperkuat demokrasi.









